PENDAHULUAN
Gagasan tentang peradaban telah banyak dieskplorasi oleh para sejarawan, sosiolog, dan antropolog seperti Max Weber, Durkheim, Tynbee, Spengler, Sorokin, Christopher Dawson, dan lain sebagainya. Ide yang dikembangkan oleh pemikir Perancis abad ke-19 ini selalu diperlawankan dengan konsep “barbarisme”. Masyarakat yang telah berperadaban dibedakan dari masyarakat primitif karena mereka adalah masyarakat urban, hidup menetap, dan terpelajar. Konsep peradaban memberikan sebuah ‘tolok ukur’ yang dijadikan rujukan dalam memberikan penilaian terhadap berbagai dinamika kehidupan masyarakat, yang selama abad ke-19, orang-orang Eropa banyak melakukannya melalui usaha-usaha intelektual, diplomatis, dan politis dalam mengelaborasi kriteria yang diterapkan pada masyarakat-masyarakat non-Eropa yang dapat mereka anggap sebagai “masyarakat yang telah berperadaban” dan mereka terima sebagai bagian dari sistem yang mendunia dalam tataran masyarakat Eropa (Samuel P. Huntington, 2005).
Peradaban merupakan entitas bentuk yang lebih luas dari kebudayaan. Namun keduanya mencakup nilai-nilai, norma-norma, institusi-institusi, dan pola pikir yang menjadi bagian terpenting dari suatu masyarakat dan terwariskan dari generasi ke generasi. Kultur dari kampung di Sumatera tentu berbeda dari kultur kampung di Sulawesi. Namun secara umum keduanya sama-sama memiliki kultur Indonesia yang membedakan mereka dari kultur perkampungan di Australia. Di sinilah Indonesia bisa menjadi sebuah peradaban. Menurut Durkheim dan Mauss, sebagaimana yang dikutip Huntington, peradaban dimaknai sebagai suatu corak wilayah moral yang melingkupi sejumlah bangsa, dengan kebudayaan masing-masing yang hanya menjadi suatu bentuk tertentu dari keseluruhan. Dapat dipahami, bahwa peradaban merupakan bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan tataran yang paling luas dari identitas budaya manusia yang dibedakan dari makhluk-makhluk lainya (Samuel P. Huntington, 2005).
Pada perspektif yang luas, peradaban-peradaban besar pada umumnya identik dengan agama-agama besar dunia. Mengapa demikian? Pengalaman selama ini membuktikan, bahwa orang-orang yang memiliki kesamaan etnis dan bahasa tetapi berbeda agama bisa saja saling membunuh satu sama lain, seperti yang terjadi di Lebanon, Yugoslavia, dan Anak Benua (Subcontinent). Karena itu, orang-orang yang memiliki kesamaan ras tetapi beda agamanya, bisa dipisahkan melalui peradaban. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang memiliki perbedaan ras tetapi memiliki kesamaan agama, bisa disatukan melalui peradaban. Arus utama agama itu ada dua: Islam dan Kristen. Pembedaan krusial antara berbagai golongan manusia berkaitan dengan nilai, keyakinan, institusi, dan struktur sosial mereka, bukan karena ciri fisikal seperti bentuk kepala dan warna kulit (Samuel P. Huntington, 2005).
Setiap gerak langkah peradaban pasti menjumpai masa perkembangan maupun kemunduran. Ia besifat dinamis sekaligus jatuh, menyatu tetapi juga saling terpisah, serta di suatu saat tenggelam dan terkubur di dalam pasir-pasir masa. Fase-fase dari evolusi peradaban dapat dipahami melalui berbagai cara. Quigley melihat, bahwa peradaban-peradaban berkembang melalui tujuh tahapan: percampuran, pergerakan, perluasan, masa konflik, kekuasaan universal, keruntuhan, dan invasi.
Menurut Huntington, pada sudut pandang yang ekstrem, sebuah peradaban dan entitas politik bisa saja saling dipertemukan. Tionghoa menurut Lucian Pye adalah sebuah peradaban yang cenderung menjadi negara. Jepang adalah sebuah peradaban yang telah menjadi sebuah negara. Sebagian besar peradaban, bagaimanapun juga, memiliki lebih dari satu negara atau entitas politik. Dalam dunia modern, sebagian peradaban meliputi dua negara atau lebih. Banyak ilmuwan yang mengkalisifikasikan berbagai macam peradaban di dunia. Namun ada “suatu kesepakatan yang masuk akal”, Melko menyimpulkan setelah meninjau kembali berbagai referensi yang berkaitan dengan kurang lebih 12 peradaban besar yang masih eksis. Tujuh peradaban tidak lagi eksis yaitu Mesopotamia, Mesir, Kreta, Klasik, Byzantin, Amerika Tengah, Andea. Lima peradaban masih eksis yaitu Tionghoa, Jepang, India, Islam, dan Peradaban Barat (Samuel P. Huntington, 2005).
PERADABAN BARAT DAN PERADABAN TIMUR
Menjadi persolan tersendiri ketika ada dikotomi antara term “Barat” yang hingga kini selalu diidentikkan dengan superior (kuat) dan term “Timur” yang hampir lekat dengan kategori inferior (lemah). Istilah “Barat” secara umum digunakan untuk menunjukkan apa yang disebut dengan agama Kristen dan “Timur” untuk menggambarkan agama Islam.
Barat dengan demikian adalah sebuah peradaban yang dipandang sebagai ‘penunjuk arah’ dan tidak diidentikkan dengan nama orang-orang tertentu, agama, atau wilayah geografis. Sedangkan Timur bisa dikatakan sebagai pihak yang mengikuti atau mengekor ke mana saja ‘penunjuk arah’ itu bergerak. Pengidentifika-sian ini mengangkat peradaban dari historisitas, wilayah geografis, dan konteks kulutralnya (Samuel P. Huntington, 2005). Secara historis, peradaban Barat adalah peradaban Eropa yang diwakili oleh Yunani-Romawi dan peradaban Timur adalah peradaban jazirah Arab yang diwakili Mesir, Cina, dan India.
Di era modern, peradaban Barat adalah peradaban Eroamerika (Euroamerican) atau Atlantik Utara. Eropa, Amerika, dan Atlantik Utara dapat dijumpai di dalam peta, sedangkan Barat tidak. Sebutan “Barat” juga digunakan untuk menunjukkan pada konsep “westernisasi” dan hal ini telah memberikan penafsiran yang menyesatkan dalam kaitan dengan westernisasi dan modernisasi (Samuel P. Huntington, 2005). Pada akhirnya, akan dipaparkan secara detail tentang peradaban Barat dan Timur dalam perspektif kaum orientalis dan oksidentalis. Masing-masing memiliki pandangannya yang berbeda-beda.
Perspektif Kaum Orientalis
Menurut kaum orientalis, peradaban Barat merupakan pusat perada-ban yang harus diikuti oleh peradaban-peradaban yang lain. Orang di luar peradaban Barat harus bercermin untuk bisa menjadi seperti peradaban Barat. Karena itu, ada anggapan bahwa hampir sebagian besar penerima hadiah Nobel adalah orang-orang Timur (Asia, Afrika) dengan asumsi, seseorang dikatakan bisa sama kedudukannya dengan Barat ketika telah menerima hadiah Nobel. Karena itu, cara untuk menggambarkan dunia Timur adalah melalui penelitian terhadap ilmu, tradisi, peradaban, dan kebudayaan Islam. Tujuannya adalah untuk menyelami rahasia, watak, sifat, pemikiran, sebab kemajuan, dan kekuatan masyarakat Islam (Abdul Fattah, 1997).
Bagi kaum orientalis, Timur adalah sesuatu yang eksotis, erotis, asing, sebagai fenomena yang bisa dimengerti, bisa dipahami dalam jaringan kategori, tabel, dan konsep, yang melaluinya Timur terus-menerus dibatasi dan dikontrol. Para orientalis telah menciptakan tipologi watak, menyusun perbedaan antara Barat yang rasional dan Timur yang malas (Bryan S. Turner, 2002). Para orientalis klasik memposisikan dirinya sebagai “ego” yang menjadi subyek dan menganggap non Barat sebagai “the other” yang menjadi obyek. Karena pembedaan kategori ini, muncul kategori superioritas dalam “ego” Eropa, sedangkan akibat posisinya sebagai obyek yang dikaji juga mengakibatkan munculnya kategori inferioritas dalam diri “the Other” non Eropa (Hassan Hanafi, 2000).
Hingga saat ini, minat Barat untuk mengkaji tentang dunia Timur dan ketimuran dan bidang keislaman sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya institusi dan berbagai media Barat yang melakukan kajian keislaman. Hasil-hasil kajian mereka banyak beredar dan tersebar luas di masyarakat (baik di negara-negara Barat maupun di Timur), serta tertuang dalam ensiklopedia, kamus, buku, artikel, jurnal, dan sejumlah majalah lainnya. Untuk konteks Indonesia, diakui atau tidak, karya dan pemikiran mereka telah banyak dikonsumsi masyarakat umum, terutama oleh warga akademisi (Dadi Nurhaedi, 2003).Apalagi dengan adanya teknologi semacam internet yang semakin mempermudah arus informasi tentang kajian-kajian orientalis. Belum lagi adanya buku-buku terjemahan yang semakin mempercepat pemahaman para pembaca dan masyarakat luas yang mengalami kendala bahasa.
Dapat digambarkan, bahwa kaum orientalis memposisikan peradaban Barat selalu pada posisi kuat dan memposisikan peradaban Timur hampir pasti lemah. Timur harus dikonsepsikan kembali jati dirinya sebagai Timur dalam perspektif Barat. Karena itu, menurut mereka, Timur harus banyak bercermin pada peradaban Barat dalam berbagai aspeknya. Kalau tidak, maka Timur akan tetap menjadi terbelakang dan tidak bisa menyeimbangi Barat.
Perspektif Kaum Oksidentalis
Menurut kaum oksidentalis, eksistensi peradaban Barat sekarang tidak bisa terlepas dari historisitas masa lalunya yang hingga kini sumber-sumbernya masih disembunyikan. Mereka tidak ingin mengungkapkan (kalau tidak mau disebut menyembunyikan dengan malu-malu) siapa sebenarnya dan bagaimana pembentukan Barat (baca: Eropa) hingga menjadi seperti sekarang ini.
Seorang intelektual terkemuka dan kontroversial asal Mesir, Hassan Hanafi menjelaskan, bahwa Eropa yang kini berdiri kokoh telah memiliki dua sumber kesadaran yang disembunyikannya dan tak terekspos. Kedua sumber itu adalah sumber Timur Lama dan lingkungan Eropa. Timur Lama di sini meliputi Cina, India, Persia, dan Peradaban Mesopotamia (Babilonia, Asyiria, Accad), Syam (negara Kan’an), dan sumber-sumber dari seluruh benua Afrika dan peradaban Islam yang muncul dalam filsafat skolastik pada masa akhir abad pertengahan. Lingkungan Eropa meliputi agama-agama paganis di Eropa yang dimulai pada abad kedua sebelum tersebarnya agama Kristen, mitos, tradisi, budaya, letak historis, lingkungan geografis Eropa yang merupakan perpanjangan Asia ke arah Barat dan perpanjangan Afrika ke arah utara (Hassan Hanafi, 2000).
Secara geografis, historis, dan peradaban, Eropa merupakan perpanjangan Asia ke arah Barat. Bahasa Hindia-Eropa pun berasal dari Asia Tengah. Di samping sebagai alat komunikasi, bahasa mencerminkan ciri pemikiran, konsepsi tentang alam, dan nilai-nilai moral. Ketika Timur menjadi pusat peradaban dunia di bidang politik, sosial, ekonomi, agama, hukum, ilmu pengetahuan, sastra, kesenian, industri, sejarah dan filsafat, agama-agama di Timur telah mempengaruhi agama di Romawi. Muncullah agama-agama yang berasal dari Timur seperti Cybele dari Asia Kecil, agama Serapis dari Mesir yang berpindah ke Yunani dalam format baru, Phrygion yang ritus-ritusnya selalu muncul dalam perayaan musim semi, tuhan-tuhan Mabellona, dan lain sebagainya. Romawi mengadopsi ritus-ritus Mesir dan hari-hari besarnya. Hal inilah yang memberi warna baru dalam kesadaran Romawi (Hassan Hanafi, 2000).
Filsafat Yunani sendiri tidak bisa terlepas dari pengaruh Asia Kecil yang secara geografis dan historis bersinggungan dengan peradaban Mesopotamia dan agama Timur, utamanya dari Persia. Legenda Siris, Osiris, dan Horus sangat popular dalam mitologi Yunani. Phitagoras pun mengenal matematika Timur dan tasawufnya. Plato pernah belajar di Memphis selama kurang lebih lima belas tahun. Bahkan bisa jadi teorinya yang terkenal tentang idea diambil dari teori kesenian Mesir Kuno. Hanya saja teori kesenian Mesir Kuno diterapkan dalam lukisan yang kasat mata, sedangkan teori Plato berupa pemikiran yang abstrak (Hassan Hanafi, 2000).
Seluruh aspek iluminis tasawuf dalam filsafat Yunani, termasuk esoterisme Socrates, kontemplasi Thales, dan pakar fisika awal tentang kejadian alam dan kehidupan, merupakan kelanjutan peradaban Timur. Astronomi, ilmu sihir, dan dunia para normal di Yunani juga berasal dari Babilonia. Di India juga ditemukan ilmu hitung, meskipun seolah-olah ada kesan Phitagoras dan Thales tidak pernah berinteraksi dengan sekte-sekte di Timur. Selain berada di belakang sumber Yunani-Romawi, Timur Lama juga berada di belakang sumber Yahudi-Kristen. Taurat merupakan kumpulan literatur yang mempunyai padanan dalam literatur Babilonia, Asyiria, Accad, dan Kan’an. Mitologi Ibrani lama berasal dari mitologi Mesopotamia (Hassan Hanafi, 2000).
Sumber Islam dalam kesadaran Eropa hampir tidak pernah disebutkan. Karena Islam dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran Eropa. Islam lebih dekat ke Timur daripada Barat walaupun sebenarnya tingkat penyebaran Islam ke Timur sama dengan penyebaran ke Barat. Islam ada di seperempat bumi Eropa, di Andalusia, bagian utara Perancis, bagian utara Italia, Sicilia, Crete, Yunani, Cyprus, dan Eropa Timur. Ilmu pengetahuan Islam terutama filsafat, kalam, ilmu alam, matematika, menjadi salah satu penyangga kebangkitan Eropa modern (Hassan Hanafi, 2000).
Salah satu penyebab disembunyikannya sumber-sumber tak terekspos adalah rasialisme yang terpendam dalam kesadaran Eropa. Rasialisme inilah yang menjadikan Eropa enggan mengakui eksistensi orang lain. Eropa diklaim sebagai pusat dan menempati puncak kekuatan serta menjadi pioner di dunia. Rasialisme bangsa Eropa terlihat jelas dalam ideologinya di abad lalu seperti nasionalisme, nazisme, fasisme, dan zionisme. Namun demikian, terungkaplah bahwa sumber-sumber kesadaran Eropa berasal dari Cina (Nedham), India (Nakamura), Islam (Garaudy), dan Timur Lama (Toynbee) (Hassan Hanafi, 2000).
Barat sebagai peradaban yang kosmopolit merupakan mitos yang harus dihancurkan kaum oksidentalis. Dengan metode fenomenologi dan dialektika-historisnya Hanafi, posisi Barat ingin dikembalikan pada posisi sejajar dalam peradaban manusia. Alhasil, tidak akan ada pusat peradaban dan cabang peradaban. Semua peradaban berada pada posisi yang sederajat. Satu sama lain saling berlomba untuk mencari yang terbaik. Kaum oksidentalis ingin mendudukan Barat sebagai obyek kajian, lalu melakukan pembebasan diri dari hegemoni Barat yang sarat kepentingan, dan pada akhirnya menghancurkan mitos bahwa Barat sebagai “kebudayaan kosmopolit”. Alhasil, terjadilah kesetaraan antar-peradaban. Cita-cita kaum oksidentalis tidak licik seperti kaum orientalis.
MEMBACA INDONESIA: SEJARAH SELALU BERULANG
Berdasarkan klasifikasi peradaban yang telah dijelaskan di atas, bahwa suatu peradaban itu terdiri dari berbagai macam kebudayaan, agama, serta norma-norma yang berlaku, maka Indonesia dalam konteks ini ditempatkan sebagai sebuah peradaban. Indonesia yang lebih kuat namanya dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki ragam adat-istiadat, bahasa, dan ras dari Sabang hingga Merauke. Mungkin tidak semua warga negara Indonesia mengenal apa saja macam-macam bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indonesia, baik yang di Sumatera maupun yang di Papua. Bahkan dalam satu provinsi, sebagai misal, seorang warga ada yang tidak paham bahasanya, karena beda dialek. Bagaimana mau tahu jumlah perbedaannya, lha wong untuk mengetahui antar-desa saja sudah susah, apalagi antar pulau.
Pada persoalan bahasa saja, untuk bahasa Jawa sangat beragam jenisnya. Ada Jawa kromo inggil, Jawa kasar, Jawa ngapak, Jawa ala Jogja, dan Jawa ala Surabaya (arek-arek). Istilah “kamu” dalam bahasa Jawa cukup banyak, seperti: Sampeyan, panjenengan, kowe (kasar), dan lain sebagainya. Pada bidang agama, Indonesia sekarang telah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghu Chu. Ini yang diakui, yang tidak diakui bahkan kelahiran agamanya sempat menjadi kontroversial juga mewarnai peradaban bangsa Indonesia. Itu yang nampak dalam permukaan, yang tidak nampak tidak boleh dianggap remeh begitu saja. Justru keragaman inilah yang mewarnai Indonesia untuk menjadi sebuah peradaban tersendiri.
Kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur lebih dari enam dekade tentu memiliki sistem pemerintahan yang selalu berganti-ganti. Mulai dari demokrasi pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin ala Soekarno, rezim otoriter Orde Baru (state qua state, neo-patrimonialism, bureucratic polity, sampai dengan limited pluralism), hingga akhirnya memilih demokrasi sebagai asas pemerintahan.
Indonesia merupakan negara terbesar nomor empat di muka bumi ini. Ketika makalah ini ditulis, Indonesia telah merdeka menjadi negara lebih dari 63 tahun, walaupun pada kenyataannya Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tetapi mengakuinya pada tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda.
Apa yang kita alami dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, menurut Amin Rais, sesungguhnya hanya pengulangan dari apa yang yang kita alami pada zaman penjajahan kompeni dan pemerintahan Belanda di masa lalu. Perbedaan antara tempo doeloe dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format belaka. Dahulu pendududkan fisik dan militer Belanda menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian, dan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pertahanan. Sedangkan sekarang ketika penjajahan itu tidak dalam bentuk fisik lagi tetap saja kemandirian dan kedaulatan Indonesia sebagai negara tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing (Amin Rais, 2008).
Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte bukan saja perekonomian nasional seperti kebijakan perdagangan, keuangan, perbankan, penanaman modal, kepelayaran dan kepelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas dan non-migas, dan lain sebagainya, tetapi juga kebijakan politik dan pertahanan. Bahkan bisa dikatakan, bahwa bangsa Indonesia telah tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Negara kita begitu cepat lupa pada sejarah. George Santayana, filsuf Spanyol berpendidikan Amerika pernah mengingatkan, bahwa mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu. Ada juga pepatah asing yang sangat terkenal, sejarah berulang kembali. Kalau kita mau jujur melihat hilangnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita, sesungguhnya sejarah imperealisme tempo dulu kini sudah hadir kembali dalam bentuk dan pengejawanta-han yang berbeda. Agaknya banyak di antara kita yang belum atau tidak menyadari-nya. Seorang dramawan dan sosialis Irlandia, George Bernard Shaw (1856-1950) mengatakan, bahwa manusia merupakan makhluk yang unik dan agak aneh, sekalipun sejarah selalu berulang, manusia sangat sulit bahkan tidak mampu untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk. Karena itu, menurut guru besar ilmu politik ini, sejarah merupakan kontinuitas antara masa lalu, masak kini, dan masa depan (Mohammad Amin Rais, 2008). Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Kita pasti ingat, pada awal abad ke-17, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mulai menjajah kita dan diteruskan oleh pemerintah Belanda sampai menjelang akhir perang dunia II. Bahkan Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pada tahun 1947 dan 1949. Mereka pada akhirnya berhasil menduduki kepulauan Indonesia dan mengusai hasi bumi, terutama rempah-rempah dan perkebunan Indonesia, sampai sekitar tiga abad. Ketika VOC bangkrut pada 1799. pemerintah Benda mengambil alih kegiatan VOC di Indonesia. VOC adalah korporasi multinasional pertama dalam sejarah dan merupakan perusahaan pertama yang menerbitkan saham (Amin Rais, 2008).
Secara bertahap VOC menjadi sebuah kekuasaan teritorial. Pada abad ke-19 kekuatan-kekuatan ekonomi Eropa, sebagai produk kapitalisme industrial, akhirnya menjadi unsur pokok dalam gelombang baru imperealisme Eropa. Untuk memperta-hankan imperealisme dan kolonialisme mereka, negara-negara Barat memerlukan komponen-komponen penopang berupa perbankan, media massa, dan dukungan elit nasional bangsa yang terjajah. Hakikatnya, korporatokrasi pada awal abad ke-21 merupakan turunan dari korporatokrasi empat abad silam. Hanya saja yang sekarang ini tentu lebih canggih dan seringkali bersifat terelubung, tetapi daya hancurnya mungkin justru lebih besar (Mohammad Amin Rais, 2008).
Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos bersifat reaksioner, berhenti, dan tidak pernah berubah. Sedangkan sejarah berwatak dinamis dan seringkali memunculkan perubahan-perubahan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu, sekalipun sejarah cenderung selalu berulang, pengulangan itu sesuai dengan perkembangan zaman, dapat bersifat lebih fundamental, radikal, dan destruktif. Imperealisme ekonomi ternyata dapat muncul kembali sambil menunggangi proses globalisasi dengan daya eksploitasi dan destruksi yang lebih luas (Amin Rais, 2008).
Bila dicermati, mengapa VOC dan pemerintah Belanda dapat menjajah Indonesia. Tentu karena elit dan penguasa Indonesia saat itu (katakanlah para raja) tidak semuanya melakukan perlawanan bersama rakyat untuk memukul balik kaum imperealis-kolonialis. Tetapi justru sebagian dari mereka berkolaborasi dengan pihak penjajah. Tentu para pahlawan semisal Sisingamangaraha, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan lain sebagainya telah berjuang keras untuk bangsa ini. Akan tetapi ada juga lapisan aristrokasi yang cenderung berdamai dan bahkan menjadi subordinat atas kompeni dan penjajah Belanda. Mereka bahkan mengumpulkan pajak atas nama pemerintah Hindia Belanda (Amin Rais, 2008). Sungguh amat kejam.
Cerita di atas akan menjadi lain ketika para aristokrasi Indonesia saat itu secara serempak bersama rakyat melakukan perlawanan terhadap para kompeni Belanda. Jelas, ini menjadi kesulitan besar bagi mereka untuk masuk ke Indonesia. Jika kekuatan perlawanan itu diterapkan untuk konteks sekarang, maka mustahil kekuatan-kekuatan korporatokrasi itu mengacang-acak dengan gampang kedaulatan ekonomi kita. Namun sayang, para elit penguasa kita malah tunduk (kalau tidak ingin disebut ketakutan) dari para korporatokrasi asing itu.
Membongkar mentalitas inlander ternyata tidak mudah. Semangat kemandirian dan rasa percaya diri yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Syahrir, dan lainnya kin entah terbang ke mana. Sekeping contoh dapat disebutkan di ini, ketika Presiden Bush ingin melakukan kunjungan ke Indonesia, sebagian pemimpin besar bangsa ini malah “ketakutan” dan merasa panas dingin. Pengamanan yang diberikan kepada Presiden AS yang di negerinya sendiri sudah tidak populer itu sungguh berlebihan dan sekaligus agak memalukan. Tidak ada negara mana pun di dunia yang menyambut Presiden Bush seperti maharaja diraja, kecuali di Indonesia sekarang ini. Seolah Indonesia telah menjadi vazal atau negara protektorat AS (Amin Rais, 2008).
PSEUDO CIVILIZATION, LABEL BARU UNTUK INDONESIA
Sejak pra kemerdekan hingga menjadi negara yang berdaulat dan terbebas dari jajahan Belanda, Indonesia tidak bisa melepaskan sisa-sisa jajahannya, begitu juga warisan-warisan bangunannya. Sudah enam dekade Indonesia merdeka, tetapi warisan penjajahan tetap berlaku di Indonesia, bahkan model penjajahan itu dilakukan oleh sesama warga negaranya, baik itu oleh pemerintah terhadap rakyat atau militer terhadap warga sipil. Sejarah telah membuktikan bahwa kekejaman itu pernah dilakukan rezim pemerintah terhadap rakyat seperti yang terjadi pada peristiwa G 30S PKI (1965), kasus Malari, Tregedi pembantaian Tanjung Priok dan Talangsari, serta pembunuhan aktivis pro-demokrasi 1998 dan seorang aktivis HAM, Munir. Hal ini menunjukkan, bahwa warisan penjajan Belanda masih diberlakukan oleh sesama anak bangsanya sendiri.
Kita tentu akan bangga ketika tim sepak bola merah putih berlaga melawan kesebelasan asing di Kejuaraan Piala Asia tahun 2007, Stadion ISTORA seolah-olah mau runtuh. Teriakan dan tepuk tangan membahana, di dalam dan di luar stadion, yang mendukung kesebelasan merah putih sulit disaingin oleh bangsa Asia lainnya. Luar biasa. Setiap kali tim merah putih ini memperoleh medali emas, kita bangga bukan main, tetapi kalah kita kecewa besar. Ketika akhirnya Indonesia memperoleh urutan keempat di bawah Thailan, Vietnam, dan Malaysia, kita sedih berhari-hari (Amin Rais, 2008).
Apakah kita salah jika kita memuja-muja tim merah putih ketika bertarung di gelanggang olah raga regional atau internasional? Tidak salah sama sekali. Memang sudah seharusnya demikian. Akan tetapi mengapa nasionalisme olah raga seperti tidak ada kaitannya dengan nasionalisme ekonomi, nasionalisme politik, nasionalisme pertahanan-keamanan, nasionalisme pendidikan, dan nasionalisme di bindang yang lainnya. Bila diibaratkan sebuah rumah di pinggi jalan, maka olah raga itu bagian pagar depan yang selalu dilihat terus oleh semua pengguna jalan raya. Pemerintah kita seperti pemilik rumah di pinggir jalan raya itu. Dia hanya memiliki obsesi, bagaimaan pagar rumah terlihat bersih, mengkilat, dan tidak indah dipandang. Selain itu masa bodoh. Ketika perabotan rumah dicuci orang lian, ia tidak peduli. Bahkan ketika anak dan istrinya dibawa keluar oleh orang lain, si pemilik rumah tidak mengambil tindakan apa pun. Ia hanya bisa menonton, seolah tak ada sesuatu yang perlu dirisaukan. Yang penting, pagar rumah terlihat bagus. Kira-kira demikian gambaran yang sedang menimpa negara kita (Amin Rais, 2008).
Kedaulatan nasionalisme kita hanya sekadar kedaulatan simbolik. Sangat dangkal. Semua hanya nampak pada permukaan saja. Ketika kekayaan alam kita dikuras dan dijarah oleh korporasi asing, ketika sektor-sektor vital ekonomi seperti perbankan dan industri asing, bahkan ketika kekuatan asing sudah dapat mendikte perundang-undangnan serta keputusan-keputusan politik, kita diam membisu. Seolah sudah kehilangan harga dan martabat diri (Amin Rais, 2008). Ketika kebudayaan kita secara perlahan-lahan tergantikan dengan kebudayaan luar negeri, kita enggan menanggapinya dan diam-diam mengikuti budaya dari luar negeri tersebut. Bahkan bangga jika kita menggunakan produk-produk mereka. Jika hal yang demikian telah terjadi, bagaiaman kedaulatan dan kemandirian nasional kita di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ketiga indikator inilah yang akan label pada Indonesia sebagai negara yang pseudo civilization.
Kedaulatan Ekonomi-Politik
Dr. Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya neo-kolonialisme. Dalam pidatonya di depan the Asia HRD Congress di Jakarta, 3 Mei 2006, Mahathir mengatakan:
Neokolonialisme bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada di bawah kontrol agen-agen yang dikendali-kan oleh mantan penjajah kita (Amin Rais, 2008).
Mahathir mengingatkan, bila negara-negara Asia ingin maju, mereka harus merubah mindset atau tata-pikir mereka agar benar-benar merdeka dan berdaulat. Tata-pikir bangsa-bangsa Asia yang dijajah sampai berabad-abad telah menjadi kuat terpola dan berurat-berakar. Betapa tepatnya pandangan Mahathir itu. Kita seringkali melihat cara berpikir dan bertindak sebagian anak bangsa yang bagaikan beo dan (maaf) monyet yang selalu meniru-niru apa saja yang datang dari Barat (Amin Rais, 2008).
Karena para majikan dan pemikir ekonomi asing mengatakan, bahwa sistem ekonomi yang paling produktif adalah sistem yang ramah pada pasar, maka sebagian dari kita mengkhotbahkan seruang agar ekonomi Indonesia berwata market-friendly. Mereka seolah lupa kalau pasar tak pernah punya nurani. Ideologi pasar adalah seratus persen mencari profit tanpa ada pertimbangan apa pun juga. Joseph Stiglitz mengingatkan teori invisible hand atau tangan tidak kelihatan dalam ekonomi pasar sesungguhnya tidak nyata. Karena “tangan” itu memang tidak ada. Amin Rais pernah terkenjut ada sekorang ekonom Indonesia yang mungkin ilmuny masih nanggung, menganggap Stiglitz dan pendahulunya bodoh. Bodoh karena keduanya berpendirian, bahwa ekonomi pasar dapat lebih berfungsi bila pemerintah melakukan intervensi agar dapat lebih efisien di samping dapat mengurangi pengangguran.
Paham neoliberalisme telah merajalela di negara Indonesia tanpa ada perlawanan dari internal. Bahkan pemerintah secara malu-malu (kalau tidak mau disebut setuju) mendukung regulasi yang berpihak pada pasar. Walaupun tidak ada undang-undang yang mendukung adanya privatisasi aset-aset negara, tetapi secara personal para elit pemerintah memberikan dukungan tersebut. Bahkan akhir-akhir ini menteri BUMN ingin memprivatisasi lembaga-lembaga negara sehingga pemerintah tidak harus membuat regulasi tersebut. Banyak pula perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tetapi pemiliknya dari luar. Free Port, Excon Mobil, Indosat, Blok Cepu, dan Aqua (Danone) menjadi sederet bukti bahwa sebagian aset Indonesia telah menjadi milik orang lain. Entah apa lagi yang akan dijual oleh mereka yang ingin mengambil keuntungan dari negeri ini. Sebuah sikap yang kontras dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sudah lebih setengah abad Indonesia merdeka, tetapi kedaulatan ekonomi tidak pernah berada di tangah rakyat.
Kita masih ingat bagaimana Indonesia tunduk pada WTO untuk menerima impor paha ayam dari AS sehingga ribuan peternak ayam kita serentak gulung tikar. Demikian juga Indonesia begitu taatnya membuka diri tanpa ada proteksi terhadap impor gula, tekstil, dan berbagai komoditas lain yang merugikan rakyat Indonesia sendiri. Sikap konyol Indonesia ini jarang ditandingi oleh negara lain. Inilah doktri globalisasi yang hingga kini masih diyakini oleh sebagian aristokrasi banga kita. Doktrin itu meliputi: liberalisasi perdagangan dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal, dan pasar tenaga kerja, dan merampingkan (downsizing) peran negara, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan sosial dan ekonomi (Amin Rais, 2008).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem perekonomian Indonesia ingin dibawa-bawa pada liberalisasi ekonomi. Pemerintah disetir untuk membuat kebijakan yang pro terhadap pasar. Dalam konteks negara yang sedang berkembang, Indonesia ingin menerapkan sistem kapitalisme dan benar-benar mempersempit peran negara atau bahkan bila perlu tidak ada sama sekali. Namun sayang, sistem kapitalisme yang berkembang di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya (kecuali Singapura) tidak menjadi kapitalisme yang tulen, tetapi sekadar apa yang disebut Yosihara Kunio sebagai kapitalisme semu (ersatz kapitalism). Meminjam istilah Arief Budiman, kapitalisme semu bararti kapitalisme yang tersubstitusi dan lebih inferior.
Persoalan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya benar-benar diberlakukan konsep developmental state sebagaimana yang telah berlaku di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Asia Timur. Konsep ini merupakan suatu paradigma yang mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan ekonomi dengan secara langsung mengintervensi proses pembangunan (yang berbanding terbalik dengan cara berpikir yang mengandalkan kekuatan pasar) dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Paradigma ini membangun tujuan substantif sosial dan ekonomi yang memandu proses pembangunan dan mobilisasi sosial. Karakteristik dari paradigma ini adalah negara yang kuat, peran dominan pemerintah, rasionalitas teknokratik dalam pembuatan kebijakan ekonomi, birokrasi yang otonom dan kompeten serta terlepas dari pengaruh kepentingan politik (Yogi Suwarno, 2006).
Ketidakberdayaan sitem perekonomian Indonesia tidak lain karena masih banyaknya pihak-pihak yang melakukan perburuan rente (rent-seeking) yang dalam penjelasan Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, perburuan rente itu merupakan usaha yang dilalui tidak secara alami namun melanggar regulasi pemerintah, semisal korupsi. Keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi tujuan utama para kaum rent-seekers. Hal ini pun senada dengan apa yang dinyatakan oleh KS. Jomo, bahwa di samping pemberlakuan konsep developmental state yang telambat di negara-negara Asia Tenggara, adanya para pencari untung (rent-seeking) juga merajalela di belahan negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia.
Karena itu, kita harus berani mengembalikan kedaulatan ekonomi yang sejak beberap waktu lalu selalu mengekor kepada sistem perekonomian Amerika. Kita harus secara serempak berani berteriak melawan tiga pilar institusi globalisasi: IMF, WTO, dan World Bank. Kita jangan mengulang kembali sejarah pascakrisis moneter yang melanda Indonesia akhir 1990-an, di mana Indonesia pernah didikte dan didominasi oleh IMF. Hampir semua koran baik dalam maupun luar negeri memuat berita ketidaberdayaan ini (saat di bawah kepemimpinan Soeharto).
Kedaulatan Budaya
Secara sederhana budaya adalah buah pikiran atau hasil akal budi (KBBI, 1990). Kebudayaan (culture) adalah konsep yang telah tua. Kata latinnya, cultura, menunjuk pada pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanaman atau ternak. Istilah itu selanjutnya telah berubah menjadi gagasan tentang keunikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Berkembang lebih lanjut, ia menjadi multidimensi bersama dengan munculnya berbagai pendapat tentang apa makna perbedaan dan keunikan-keunikan itu dalam memahami manusia umumnya sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 (www.kompas.com, 2003).
Menurut John Storey, ada tiga pengertian tentang budaya sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Raymond William. Pertama, budaya merupakan suatu proses umum perkembangan intelektual, spritual, dan estetis. Misal kita berbicara tentang budaya orang Indonesia dengan merujuk pada faktor-faktor intelektual kaum cendekiawannya, spiritualitas para agamawannya, senimannya, serta para penyair-penyair besarnya. Kedua, budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu. Pengertian ini tidak hanya terpaku pada perkembangan intelektual, spritual, dan estetis saja. Tetapi juga mencakup perkembangan sastra, hiburan, olah raga, dan upacara ritual agama tertentu. Ketiga, budaya pun bisa merujuk pada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Teks-teks dan praktik-praktik itu memiliki fungsi untuk menciptakan makna tertentu, misal puisi, novel, balet, opera, dan luiksan (John Storey, 2003).
Indonesia telah memiliki penduduk lebih dari 220 juta jiwa yang berdiam di 6.000 pulau di antara 17.667 pulau besar dan kecil. Memiliki sekitar 200 bahasa dan dialek lokal, 350 kelompok etnis dan adat istiadat yang tentu berbeda-beda. Agama pun ada enam: Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Budaya di masing-masing daerah tentu berbeda satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Keanekaragaman itu menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia.
Namun, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia di atas tidak bisa berdiri tegak di negerinya. Kebudayaannya seolah menjadi asing di negerinya sendiri. Justru budaya yang berkembang dan akrab dalam kehidupan sehari-hari adalah kebudayaan yang datang dari luar atau yang akrab kita sebut sebagai budaya barat (west culture). Budaya inilah yang pada akhirnya menghantui masyarakat Indonesia. Inilah salah satu bentuk keberhasilan dari apa yang telah dikonstruksikan oleh kaum orientalis dalam mengkaji dunia ketimuran. Mereka mengkonstruksikan, bahwa Barat adalah pusat kebudayaan yang harus menjadi cermin kebudayaan yang non Barat. Indonesia yang menjadi salah satu kebudayan non Barat harus berkaca kepada Barat. Konstruksi inilah yang telah menjadi main set masyarakat kekinian.
Pada akhirnya, generasi muda merasa bangga ketika menjadi komprador-komprador dari aset-aset asing. Barang-barang dari luar negeri dengan begitu mudah masuk ke Indonesia tanpa ada regulasi yang jelas. Pasar bebas pun telah berkelana di negara yang kaya akan sumber alamnya. Kalau boleh dikata, bendera neoliberalisme telah berkibar di negeri ini. Perusahaan-perusahaan besar seperti McDonal, KFC, Fred Chiken, Pizza Hut, dan lain sebagainya telah bertengger bebas di setiap jalan-jalan di kota-kota besar Indonesia. Hal ini berdampak pada tersingkirnya sektor ekonomi informal dari masyarakatnya sendiri (kalau tidak mau disebut ditinggalkan).
Budaya Barat yang kian hari makin dimintai generasi muda dengan produk-produknya yang menghipnotis, menjadikan budaya lokal kita mati kutu dan dijauhi (kalau tidak boleh dibilang dibenci) oleh warganya sendiri. Kita seolah tidak lagi bangga dengan keanekaragaman budaya yang sangat multietnis, bahkan malu jika melestarikan kebudayaan kita di hadapan teman yang lain. Kita bisa melihat dalam industri musik, tidak jelasnya aliran yang mereka anut bahkan hampir mendekati dan menyerupai gaya-gaya musik Barat. Dalam dunia pentas seni, tontonan wayang kulit, ketoprak, atau pun jenis pentas seni lainnya telah dikalahkan dengan sejumlah layar lebar yang datang dari barat. Dalam dunia perfilman, tontonan lokal telah digeser oleh sejumlah film-film barat yang dari segi kualitas jauh lebih baik dari dunia perfilman Indonesia. Tak jarang, sistem pendidikan di negeri ini pun hanya sekadar foto copi dari sistem-sistem pendidikan yang datang dari Amerika, Jepang, atau Australia.
Selain itu, budaya pop (pop culture) telah menggurita di negeri ini. Budaya pop dapat dipahami sebagai budaya yang diproduksi oleh massa untuk konsumsi massa. Budaya massa adalah budaya yang dianggap sebagai dunia impian secara kolektif. Misalnya, hiking ke pegunungan, liburan ke pantai, dan merayakan valentine’s day bersama pacar. Bagi Idi Subandi Ibrahim, budaya pop merupakan kebudayaan massa yang populer dan ditopang oleh industri kebudayaan (cultural industry), serta mengkonstruksi masyarakat tak sekadar berbasis konsumsi, tapi juga menjadikan semua artefak budaya sebagai produk industri. Budaya massa yang terjadi disebabkan massifikasi, yaitu industrialisasi dan komersialisasi yang menuntut standardisasi produk budaya dan homogenisasi cita rasa. Dengan komersialisasi, produk budaya (massa) berubah, sejalan percepatan tuntutan pasar (Pikiran Rakyat, 15/7/05).
Masyarakat industrial, menurut Kuntowijoyo, ditandai oleh tiga hal, rasionalisasi, komersialisasi, dan monetisasi. Rasionalisasi artinya, bahwa masyarakat modern lebih mendahulukan sesuatu hal yang bersifat masuk akal daripada yang tidak masuk akal. Walaupun sebagian orang masih percaya pada dunia mistik, tetapi celah untuk berkomentar dan menyalahkan terhadap sesuatu yang tidak masuk akal terus saja terjadi. Karena itu, dentuman Rene Descartes yang berbunyi cogito ergo sum (aku berpikir, maka aku ada) benar-benar diamini oleh dunia sebagai awal dari lahirnya rasionalisme dan awal abad pencerahan, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya teknologisasi pada segala bidang hingga sekarang.
Komersialisasi menunjukkan, segala segmen kehidupan harus memiliki daya jual tersendiri. Tidak ada sesuatu yang tidak komersiil. Hal ini ditandai dengan maraknya program-program di televisi, bioskop, penjualan kaset CD, buku, dan iklan-iklan di pinggir jalan maupun di televisi. Bahkan, sekarang komersialisasi terjadi pada dunia perbukuan. Ada penulis buku yang disebabkan bukunya best seller dan difilmkan, tarif untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar atau talkshow (sekali manggung) seharga 30 juta rupiah. Itu pun di luar transport. Selain itu juga, komersialisasi terjadi pada segmen masyarakat bawah, yaitu parkir kendaraan (motor misalnya) dan buang air kecil. Untuk kedua jasa ini kita harus mengeluarkan uang seribu rupiah. Mungkin beberapa dekade ke depan, untuk buang angin (kentut) atau bernafas saja kita harus membayar.
Monetisasi mengindikasikan bahwa semua hal harus diukur dengan uang. Ini terkait erat dengan penjelasan komersialisasi di atas. Dampak dari adanya proses komersiasliasi adalah menuntut adanya proses monetisasi (uangisasi). Uang menjadi satu bentuk konkrit atas proses yang terjadi. Makanya, banyak pemilik modal yang hanya menimbun uang dari hasil larisnya penjualan produk mereka. Rakyat bawah hanya menjadi sasaran empuk dari propaganda mereka. Rakyat tidak sadar bahwa mereka telah dihipnotis dengan rayuan iklan yang hiperbolis.
Dapat dipahami, bahwa budaya pop telah hadir di tengah-tengah kita dan dalam keadaan apapun, kita harus bisa menghadapinya. Pada perkembangan mutakhir, budaya pop sudah mewabah pada urusan gaya-bergaya yang melanda masyarakat kita. Persoalan yang satu ini pun sudah menjadi pusat perhatian yang serius. Pertumbuhan gaya-bergaya mau tidak mau disebabkan adanya globalisasi ekonomi dan adanya kapitalisme konsumsi yang ditandai dengan menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan semacam shopping mall, industri fashion, industri kecantikan, industri kuliner, industri gosip, apartemen, kawasan huni mewah, real estate, gencarnya iklan barang-barang supermewah, liburan wisata ke luar negeri, dan lain sebagainya (Idi Subandi Ibrahim).
Melihat kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, anak bangsa kita masih saja
ada yang menjadi komprador-komprador dari negara asing (bahkan bangga). Mereka malah membuka cabang perusahaan asing seperti dari Prancis atau Amerika di Indonesia. Apa mereka bersalah? Karena mereka bekerja dan mencari uang untuk sanak famili mereka. Di sinilah letak tidak berdaulatnya Indonesia dalam bidang kebudayaan. Budayanya telah tergerus dan tertimbun oleh budaya asing.
Kesimpulan
Entah sampai kapan, dikotomi oposisi biner antara peradaban barat dan peradaban timur akan selalu ada. Entah sampai kapan pula, peradaban barat selalu identik dengan kemajuan dan berkuasa. Sebaliknya, peradaban timur hampir dipastikan tertinggal, miskin, dan tidak berkuasa atas peradaban barat. Dalam konteks pembicaraan ini, Indonesia telah direpresentasikan sebagai bentuk peradaban yang ada di muka bumi ini.
Sejak kemerdekaannya hingga sekarang, peradaban Indonesia masih belum bisa berdaulat. Hal ini telah dibuktikan dengan dua indikator utama, yaitu tidak berdaulatnya dalam bidang ekonomi-politik dan tidak beraulatnya dalam bidang kebudayan. Atas dasar inilah, sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai pseudo civilization.
Ridho Al-Hamdi
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UGM

Ridho Al-Hamdi
About Me
- @ridhoalhamdi
- Lecturer at Department of Govermental Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Indonesia. His interest topics are Islam and Politics, Politica Party and election Studies, political behavior, Political Communication and political marketing. Now, He resides in Yogyakarta, Indonesia. Further communication, please contact him in e-mail: ridhoalhamdi@yahoo.com
Bridging Community (Management's Class)
- Adjie Setiyawan
- Agustin Nuriel
- Ainil Izzah
- Al-Amin Reza
- Alit Unagi
- Andry Kumala
- Anne Khairunnisa
- Ardana Pratista S
- Arief Firmansyah
- Arief Wicaksono
- Arifuddin Try Utomo
- Arziannisa Azwary
- Bob Maulana
- Debi OS
- Faaza Fakhrunnas
- Fajar Praharu
- Fajar Prasetya
- Fakhrul Arief
- Gestian
- Haryo Agung P.
- Hasanuddin
- Ibnu Suryo
- Jati Pertiwi
- Khamid Rifan
- Lhia Dwi
- Lusitania Maretasari
- Luthfiyana Puspowati
- M. Noor Fahmi
- M. Siswandi
- Miftahul Jannah
- Nafta Caustine F.
- Nia Widya Ningrum
- Ova
- Putri Oktovita Sari
- Retti Mutia
- Rifqi Romadhon
- Rizkika Awalia
- Rochana K. Windati
- Sehly El Farida
- Septiara N.
- Setyasih Handayani
- Sheila Aqla RV
- T. Zeyfunnas
- Tatag Julianto
- Toga Melina Kartikasari
- Wahyu Indra
- Windi Hamsari
- Yuda Pratama Putra
Bridging Community (Economical Class)
- Agung Purnama M
- Aprinia Wardany
- Dicky Hidayat
- Dony Mahardika
- Eko Pranata
- Ericka Betty R.
- Fajar Ramadhan A
- Febri Septiawan
- Fita Fatimah
- Fitri Fauzia
- Fitri Fauziah
- Hasbi Ashshiddiq
- Ilham Farih
- Karmila PW
- Mela Melindasari
- Nita Sari Astuti
- Noor Rahmalita S
- Nopi Haryanto
- Nur Indah Hardianti
- Nuzyl Denni K
- Phian Ingdriansyah
- Puspita Maharani
- Ririd Dwi Septiani
- Said Hendra
- Setya Afriya
- Siska Budiningrum
- Tomi Putra
- Yenny Anggriani
- Yoga Prasetyo
My Followers
My Friends
- Abdul Halim Sani
- Abdul Munir Mulkhan
- Agus Wibowo GK
- Ali Usman
- Arifin "Bukan" Ilham
- Awaluddin Jalil
- Chandra
- Deni Pakek Weka
- Deni Weka
- Dharono Global TV
- Mas Jidi PECOJON
- Masmulyadi
- Masmulyadi (Dua)
- Meitria Cahyani
- Mudzakkir
- Muhammad Al-Fayyadl
- Muhibbudin Danan Jaya
- Musyaffa Basir
- P-Men IRM Sulsel
- Robby H. Abrar
- Rully
- Saiful Bari
- Tatag Julianto
Institutions
Diberdayakan oleh Blogger.
20.47
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
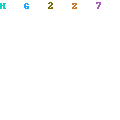
0 komentar:
Posting Komentar