
Sebagai aktivis, kita pasti kenal sosok Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib. Mereka lahir dan memang (mungkin) diciptakan untuk menentang arus, sekalipun nyawa merenggut mereka sejak berumur muda. Justru jika mereka berumur tua, mungkin ketenarannya tidak seperti sekarang ini. Mereka telah menjadi spirit dan mampu membakar semangat dan gelora generasi muda. Mampu pula menjadi inspirasi untuk melawan segala bentuk dari ketidakadilan.
Buah pikiran mereka terkadang tidak enak didengar oleh sebagian telinga orang. Bahasanya tajam, lugas, tegas, tanpa basa-basi. Tak kenal apakah mereka pejabat atau anak seorang tukang buruh. Bagi mereka semua orang tak ada bedanya. Orang baru paham akan pikiran kedua anak muda ini setelah berulang kali mencernanya. Bisakah aktivis genarasi sekarang melakukan hal yang sama dengan Gie dan Wahib? Jawabnya: Bisa! Tanyakan pada diri anda sebagai seorang aktivis.
Awalnya tidak ada keinginan untuk memperlihatkan isi pikiran dari catatan buku ini kepada orang lain. Apalagi bercita-cita untuk menerbitkannya. Namun, karena ada desakan dari teman kalau muatan tulisan-tulisannya cukup bagus, akhirnya dicoba untuk dikirim ke penerbit Resistbook. Tak diduga, naskah itu diterima begitu saja setelah dua minggu dipelajari redaksinya.
Ada empat bab, Catatan Tentang Pergerakan, Catatan Tentang Pendidikan, Catatan Tentang Agama, dan Catatan Tentang Gaya Hidup. Masing-masing dari bab berbicara secara terpisah-pisah. Setiap satu jenis tulisan selalu ada tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya. Itu artinya, menandakan kondisi pikiran penulisnya saat itu. Pada bab pertama, mengurai tentang gejolak-gejolak yang terjadi dalam sebuah gerakan atau organisasi. Terkadang kita selalu mengalami kejenuhan berorganisasi, terjadinya perdebatan antara salah dan benar, senior terlalu berkuasa dan yunior harus taat, terjadinya reshufle kepemimpinan, lemahnya pegkaderan, persoalan ideologi gerakan, hingga pemerintah.
Pada bab kedua lebih banyak melakukan kritik terhadap model pendidikan Indonesia yang tidak pernah konsisten dan tepat (soal ini bisa lebih banyak diulas oleh Mas Eko). Bab tiga mencoba menawarkan adanya konsep-konsep baru dalam agama, seperti menulis juga merupakan bagian dari jihad bahasa, sapere aude itu ijtihad, memaknai ulang keikhlasan dalam beragama, perdebatan antara Barat dan Timur yang tak kunjung usai, dan kritik terhadap Sipilis (sekulerisme, pluralismo, dan liberalisme).
Pada bagian terakhir, kita diajak untuk kembali memaknai ulang kejadian-kejadian di dalam hidup. Kita diajak untuk berbicara tentang waktu yang terkadang membelenggu kita, mengobrolkan tetang mitos malam minggu, persoalan ada dan tidaknya sugesti, hingga berbicara tentang makna kecantikan tidak mesti putih.
Semua itu tentunya dibingkai dalam frame bahwa seorang aktivis harus memiliki keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam bahasanya Kant, kita barus bersapere aude! Berani berpikir, bertindak, mengambil keputusan sendiri.
Terlepas dari itu semua, apa yang disajikan dalam buku mungil bersampul coklat dan ada gambar sepatu (kayak buku anak-anak, tapi menantang) ini bukanlah apa-apa. Dia hanya memberi spirit kepada khalayak pembaca untuk berani melakukan pemaknaan ulang terhadap realitas yang terjadi di dalam hidup.
Kita harus berani memaknai kembali sebuah realitas yang sudah mapan untuk dipertanyakan kembali. Kemudian dibuat konsepsi baru tentang realitas tersebut. Karena realitas itu milik bersama dan bisa diapakan saja. Dalam bahasanya Zuli Qodir pada pengantarnya, generasi muda harus memiliki perspektif kritis-multitafsir, karena realitas itu tidak tunggal, termasuk dalam memaknai agama (Islam).
Papringan, 29 September 2006
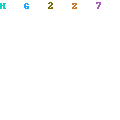

0 komentar:
Posting Komentar