 Diciptakannya pendidikan tidak lain bertujuan membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Pendidikan harus mampu mewujudkan manusia yang eksistensialis. Hal ini mengindikasikan, pendidikan harus menjadikan manusia sebagai manusia yang sedang menuju kesempurnaan atau insan kamil. Pendidikan berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal dan memahami relitas kehidupan yang ada di sekelilingnya.
Diciptakannya pendidikan tidak lain bertujuan membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Pendidikan harus mampu mewujudkan manusia yang eksistensialis. Hal ini mengindikasikan, pendidikan harus menjadikan manusia sebagai manusia yang sedang menuju kesempurnaan atau insan kamil. Pendidikan berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal dan memahami relitas kehidupan yang ada di sekelilingnya.
Dengan adanya pendidikan diharapkan manusia mampu menyadari akan potensi yang ia miliki sebagi makhluk yang berpikir. Potensi yang dimaksud adalah potensi ruhaniyah (spiritual), nafsiyah (jiwa), aqliyah (pikiran), dan jasmaniyah (tubuh). Dengan melakukan proses berpikir, manusia akan menemukan eksistensi kehadirannya sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Tidak sedikit orang yang mengartikan pendidikan sebagai proses pengajaran formal yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan dan menganggap proses penyadaran informal bukan menjadi bagian dari proses pendidikan. Hal ini jelas perspektif yang keliru dan harus diluruskan. Kita harus bisa membedakan antara pendidikan yang memiliki makna luas dengan pembelajaran yang mempunyai makna terbatas.
Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia (humanizing human) baik dalam bentuk formal maupun informal. Sedangkan pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, yakni proses transfer pengetahuan atau usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas dari dalam diri manusia. Intelektualitas dan pengetahuan itu sendiri sebenarnya belum sepenuhnya mewakili diri manusia.
Karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau peralihan ilmu pengetahuan semata. Akan tetapi dengan adanya pendidikan diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan memahami eksistensi dan potensi yang mereka miliki. Di sinilah akhir dari tujuan pendidikan, yakni melakukan proses “humanisasi” (memanusiakan manusia) yang berujung pada proses pembebasan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial mengalami dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dominasi gender maupun hegemoni budaya lain. Melihat realitas tersebut, sekiranya pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk memproduksi kesadaran dalam mengembalikan kemanusiakan manusia. Dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya pembebasan.
Namun, idealitas yang dibangun di atas berbalik arah ketika melihat realitas pendidikan dalam prakteknya. Tidak sedikit pendidikan yang justru malah membebankan peserta didik. Beban jam pelajaran di Indonesia ternyata lebih dari seribu jam per tahun. Ini diberlakukan dari SD hingga SMA. Angka ini terlama di dunia. Padahal, jumlah jam pelajaran di negara-negara Asia-Pasifik (yang bukan termasuk negara maju) hanya 900-960 jam per tahun. Negara Indonesia memang hebat, sehingga semuanya mau diambil. Nyatalah, dunia anak yang bersekolah di Indonesia sebenarnya dunia khayal, tetapi amat melelahkan. Tak memberi ruang bernapas! Padahal sebagai kiasan saja, manusia membutuhkan waktu untuk tertawa, mencurahkan isi hati, dan berlari-lari untuk mencari jati dirinya.
Belum lagi, seiring bergantinya menteri berganti pula kurikulumnya. Siapa yang berkuasa, dia berhak atas semuanya. Sebenarnya tidak masalah adanya pergantian kebijakan. Masalahnya, apakah pergantian kebijakan itu merupakan persoalan yang paling mendasar? Ternyata tidak. Banyak hal yang telah mengalami perubahan. Ujung-ujungnya berimplikasi pada pembengkakan biaya. Kalau begini, yang menjadi korban rakyat lagi. Rakyat selalu menjadi pelengkap penderita.
Ketidakprofesionalitasan guru dalam mengajar masih saja terjadi. Padahal sudah berulang kali diberikan pelatihan, hasilnya tetap nihil. Kekerasan pun terkadang tidak bisa lepas dari karakter guru yang berwatak kolot. Guru menjelaskan, siswa mencatat. Guru berbicara, siswa mendengarkan. Pengajaran bersifat monolog (satu arah). Inilah pendidikan gaya bank. Jika demikian, peserta didik tidak lain hanya duplikat dan foto copi guru. Secara tidak langsung telah terjadi pembunuhan kreativitas.
Sistem kurikulum berbasis kompetensi saja terbukti mengalami kegagalan. Banyak berita yang mengindikasikan sistem tersebut belum siap untuk diterapkan secara bersamaan. Hanya beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang mampu menerapkannya. Itu pun lembaga yang memang sudah berkelas tinggi. Bagi lembaga pendidikan pinggiran tetap saja terbelakang. Akhirnya, malah menimbulkan kesenjangan lagi. KBK hanya mempermainkan rakyat kecil. Persoalan lain juga tak terselesaikan, seperti dana BOS, sertifikasi guru, dan segudang masalah pendidikan lainnya. Idealitas tak seperti realitas. Menjadi suatu kewajaran jika ada anak didik akan mengatakan, sesuatu yang paling menyenangkan di sekolah adalah ”waktu istirahat, saat ada jam pelajaran kosong, dan ketika pulang sekolah”.
Kiranya, perlu menata ulang pendidikan yang berbasis ”keberpihakan”. Keberpihakan tentunya kepada mereka yang tertindas, mereka yang tidak mendapatkan haknya, dan mereka yang selalu menjadi korban dari pendidikan. Keberpihakan ini tentunya ingin meraih pendidikan sesuai dengan hakikatnya. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin.
Gerakan keberpihakan setidaknya telah dilakukan oleh sekolah alternatif bernama SMP Qoryah Toyyibah di Salatiga, Jawa Tengah. Sekolah ini mencoba menerapkan prinsip pendidikan murah tapi berkualitas. Prinsip ini ternyata terbukti benar. Hanya dengan SPP sepuluh ribu perbulan setiap siswa sudah bisa mengakses internet selama 24 jam. Tiap siswa mendapatkan satu komputer dengan membayar seribu perhari. Tempat belajarnya adalah alam terbuka, seperti di kebun dan di taman. Kreativitas lebih dikedepankan dan membebaskan siswa untuk berkreasi apa pun.
Pada momen bulan Mei yang bisa disandingkan dengan hari pendidikan nasional (hardiknas) inilah, pemerintah sebagai aktor perubahan pertama harus mecoba memaknai ulang hakikat dari tujuan pendidikan. Kemudian melakukan keberpihakan terhadap mereka yang belum mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Karena lembaga pendidikan sekarang sudah mulai jauh dari realitas. Mungkinkah suatu ketika guru manusia adalah alam, kemanusiaan adalah bukunya, dan kehidupan adalah sekolahnya? tanya Kahlil Gibran, penyair besar kelahiran Lebanon. Penulis menambahkan, apakah keberpihakan adalah spiritnya? Semua tergantung sistem yang berjalan.
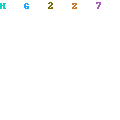

0 komentar:
Posting Komentar