 Sudah sejak kelas dua SMA dulu aku mau bikin SIM, Surat Izin Mengemudi untuk motor. Ya, sekitar
Sudah sejak kelas dua SMA dulu aku mau bikin SIM, Surat Izin Mengemudi untuk motor. Ya, sekitar Niat itu nggak kesampaian lantaran aku belum punya KTP Jogja. Di akhir kelas tiga aku mencoba membuat KTP Jogja atas nama keluarga bapak kosku, Pak Bagong. Seharian aku mengurus administrasinya dari tingkat RT, Puskesmas, hingga Kecamatan. Setelah itu menunggu satu minggu. Semua habis sekitar sepuluh ribuan.
Keesokannya aku bertanya-tanya tentang pembuatan SIM kepada Pak Bagong. Kata beliau nggak usah saja, karena hanya akan ditipu polisi.
“Nak, kamu itu gak bakalan dapat SIM kalau nggak punya uang banyak,” jelasnya sambil menyeruput kopi pahitnya.
“Lha, memang butuh duit berapa, Pak?” tanyaku heran.
“Rp 150 ribu. Itu sudah beres.”
“Kok mahal banget. Kata Pak RT cuma habis 75 ribu. Memang bapak tahu dari mana?”
“Iku, tetangga samping kosmu seminggu yang lalu baru saja buat SIM juga.”
“Ooo,” anggukku.
Niatku untuk membuat SIM tidak kesampaian, karena kondisi keuangan ngepas. Sebenarnya sih bisa kalau mau dipaksakan, tapi uang untuk makan sebulan bakal ludes.
***
Di akhir kelas tiga keinginan buat SIM muncul lagi, karena hampr kuliah. Kucoba bertanya pada Fauzan, temen sekelas, yang sudah buat.“Zan, kemarin buat SIM habis berapa?”
“Rp 180 ribu.”
“Ha!!! Bukannya Rp 75 ribu. Kok mahal sekali?” tanyaku melotot.
“Ya, memang segitu. Ceritanya, saat aku tes tertulis rambu-rambu lalu lintas dan praktek naik motor nggak lulus. Kucoba kedua kalinya tetep nggak lulus juga. Aku tanya apa yang salah, polisi itu nggak mau memberi tahu. So, aku nembak saja.”
“Trus gimana?”
“Setelah itu aku nuggu sejam, cek kesehatan, sidik jari, foto, langsung jadi.”
Lag-lagi aku urungkan niat itu lantaran kondisi keuangan ngepas. Sebenarnya sih bisa kalau mau dipaksakan, tapi uang itu untuk bayar pendafataran masuk kuliah.
Setahun kemudian, setelah aku pindah kos dan punya motor, dapat kabar kalau pembuatan SIM naik lagi menjadi Rp 200 ribu. Aku nggak habis pikir, “Kapan aku bisa buat SIM?” Padahal harga semakin naik.
Selama nggak punya SIM itu pula aku sudah ditilang empat kali. Pertama, siang hari saat pulang kuliah aku harus mengeluarkan uang dari kocek Rp 20 ribu untuk pelanggaranku itu. Kedua, menjelang shalat Subuh saat aku pulang dari sebuah pelatihan dan sengaja menerobos lampu merah. Tak diduga, nggak jauh di depanku polisi langsung menyetop. Awalnya aku harus membayar Rp 35.000. Kemudian kutawar menjadi Rp 20 ribu. Ketiga, 20 ribu saat pulang dari Parangtritis. Keempat, Rp 20 ribu lagi sepulang dari rumah teman di Bantul.
Keadaan yang demikian itu membuatku was-was jika akan mengendarai motor. Nggak nyaman. Mata harus siap sedia kalau-kalau ada cegatan. Kemudian membelokkan arah roda motor dan kabur. Usaha seperti ini kerap kulakukan. Tetapi ini bukanlah solusi yang jitu buat menangani permasalahan tidak punya SIM.
Jika ingin buat aku nggak punya uang sebanyak itu. Lagian aku gak mau juga melalui jalur licik seperti itu. Tapi, apa aku harus seperti ini terus? Selalu ditilang polisi. Bisa-bisa uang sebulan apes dan nggak bisa makan. Aku dibuat pusing sama kepolisian itu.
“Seharusnya polisi itu
***
Akhir-akhir ini aku sering menjumpai polisi melakukan rasia di jalan. Seminggu bisa dua sampai tiga kali. Keadaan ini membuatku semakin panik.
Kuputuskan saja kalau aku harus membuat SIM. Kusiapkan uang sebanyak Rp 200 ribu. Ini hasil permintaanku dari orang tua. Aku mengajak teman untuk membantu dalam proses pembuatan kartu itu. Namun, temanku melontarkan pertanyaan.
“Emang kamu sudah siap uang berapa?”
“Rp 200 ribu.”
“Nggak cukup. Sekarang naik lagi, jadi Rp 250 ribu.”
“Busyet dah, mahal amat,” celetukku sambil mengerutkan dahi.
“Mau jadi apa nggak?”
Setelah dipikir-pikir, aku tetap lanjut untuk membuat SIM. Dengan penuh pertimbangan kuambil sebagian uang jajan untuk menutupi kekurangan itu. Terpaksa bulan ini aku harus ngirit.
Jum’at, jam 10 pagi, aku dan temanku itu pergi ke Kapolres. Setelah parkir motor, bapak setengah tua itu mendekatiku dan menawarkan jasa SIM.
“Mas, buat SIM baru atau perpanjangan?”
“Buat baru, Pak,” jawabku sambil berjalan menuju arah kantor pembuatan SIM.
“Mau tak bantu nggak? Cukup Rp 270 ribu. Rp 20 ribu untuk cek kesehatan, Rp 10 untuk sidik jari. Selebihnya untuk formulir, foto, dan jasa kami.”
Dengan jawaban serinci itu aku bertambah pusing. Kucuekkan saja orang itu, lalu aku menuju ruang pembuatan SIM. Terpampang jelas di tembok, “Untuk pembuatan SIM baru Rp 75.000. Untuk perpanjangan Rp 60.000”. Tulisan lainnya, “Ingat, banyak calo! Jangan sekali-kali main curang”.
“Jika harganya segitu, selebihnya mereka apakan? Bagi hasil dengan teman sekerja? Ah, masa sih polisi, sebagai abdi negara, tega melakukan pemerasan terhadap rakyat? Nggak mungkin,” pikirku.
Aku duduk lama di bangku panjang itu sambil melihat orang sibuk dengan urusannya masing-masing.
Dengan sikap tegas aku mengambil formulir itu. kuisi lalu kuserahkan ke ruang tes. Saat tes tertulis tentang tanda-tanda lalu lintas aku bisa menjawab semua. Tes naik kendaraan gak ada salah. Kesehatan mataku baik. Aku yakin pasti lolos. Esoknya aku dipanggil dan dinyatakan tidak lolos.
“Kenapa nggak lolos, Pak?”
“
“Saat apa? Seingatku semua benar.”
“Itu katamu! Sudah nggak usah berdebat. Anda mau mengulangi lagi atau dengan cara lain?”
“Saya tes lagi saja, Pak!”
“Baiklah. Silahkan ambil formulir lagi,” jawabnya penuh ketus.
Kuambil lagi dan kuisi sesuai dengan prosedur yang ada. Saat tes tertulis dan praktek tidak ada yang salah sama seperti sebelumnya. Begitu juga dengan kesehatan mataku. Tapi, saat diumumkan tetap saja tidak lulus. Aku ngotot dan membentak polisi itu dengan menggebrak meja. Semua tatapan orang yang ada di ruangan itu terfokus ke arahku.
“Anda mau apa, Mas!” bentak polisi lain.
“Saya tidak sepakat dengan cara ini!!!”
“Lalu?”
“Saya heran dengan kedudukan polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi malah membuat bencana. Anda-anda ini
Dari arah belakang seseorang memborgol tanganku.
“Anda kami tahan, karena berlaku tidak sopan di kantor kepolisian,” jawabnya sambil memaksaku jalan menuju sel.
“Hei, saya salah apa? Mengapa mereka yang licik itu tidak ditahan,” berontakku.
“Diam. Duggg!!!”
Tiba-tida tangan polisi itu mendarat di Pundakku. Aku pingsan, tak sadarkan diri. Kemudian aku terbangun dan sudah mendapatkan diri di dalam sel. Sementara temanku masih berdebat dengan polisi itu.
“Sial. Dasar polisi keparat,” kesalku.
Esoknya aku dikeluarkan dari sel dan terdaftar di kepolisian sebagai salah satu orang yang telah berbuat tindak pidana.
“Ya sudah, Pak. Sekarang kalau mau buat SIM cepat berapa?”
“Rp 270.000.”
Kuambil uang dari saku tiga lembar seratusan ribu. Kebetulan dari kemarin aku sengaja bawa uang segitu buat jaga-jaga. Semua berjalan dengan cepat. Tak lebih dari satu jam. Formulir diisikan. Tinggal cek kesehatan dan sidik jari. Lalu foto dan menunggu pengambilan. Selesai. Setelah itu pulang.
Tak kusangka, atas nama uang mereka rela menjual simbol “Abdi Negara” kepada rakyat. Ini bukan sikap budi pekerti.
Patangpuluhan, 2 Juli 2005
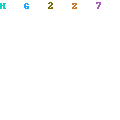

0 komentar:
Posting Komentar