 Seorang ibu penjual mie ayam di salah satu sudut utara
Seorang ibu penjual mie ayam di salah satu sudut utara Ia bukan seorang pejabat teras atas yang bisa memberikan kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Bukan seorang penulis cerdas yang mampu menuangkan pikirannya lewat media massa. Bukan pedagang yang sukses dengan meraih segala keuntungannya. Bukan pula orator yang mampu berdemo turun ke jalan. Tetapi dia seorang ibu rumah tangga dan rakyat biasa yang hanya bisa mengeluh dan menangis ketika musibah menimpanya. Tidak ada pekerjaan lain kecuali berjualan mie ayam demi menghidupi keluarganya, termasuk biaya pendidikan bagi anaknya. Si suami sekaligus kepala rumah tangga sudah meninggal.
Di wajahnya tidak ada sedikit pun senyuman yang memberi isyarat tanda kebahagiaan dan keceriaan. Setiap hari hanya mengeluh dan gelisah melihat bangsa Indonesia, bangsa yang telah menjadi darah dagingnya. Baginya, kenaikan harga BBM ini musibah terbesar yang dialami seumur hidupnya. Bu Sunarsih, demikian biasa dipanggil, mengatakan musibah ini “wes nekak gulu”. “Mending enak hidup di era Pak Harto, harga gak ada yang mahal,” demikian ia menghibur diri. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu kalau Indonesia di era Presiden Soeharto meninggalkan hutang di sana-sini.
Semua barang telah naik termasuk peralatan dan jenis bahan makanan untuk penjualan mie ayamnya. Dari harga minyak, mie mentah, dan bumbu-bumbu lainnya. Sebelum keputusan harga BBM naik, mie ayam Bu Sunarsih dua ribu rupiah. Tetapi setelah tanggal 1 Oktober 2005, saat Menteri Perekonomian Indonesia, Abu Rizal Bakrie, membacakan keputusan tentang naiknya harga BBM, harga mie ayam Bu Sunarsih menjadi dua ribu tiga ratus. Sebenarnya dia tidak tega menaikkan harga mie ayamnya, karena merasa kasihan melihat anak-anak kos yang ada di samping kanan-kirinya kurang mampu secara finansial. Tetapi harus bagaimana lagi. “Kalau tidak dinaikkan, saya tidak bisa belanja,” demikian akunya dengan penuh gelisah. Di tengah kegelisahan ini masih ada orang yang merasah kasihan kepada orang lain. Inilah sebuah perbuatan mulia yang patut ditiru.
Sambil mengaduk mie ayamnya, ibu itu terus mengomel dengan para pembelinya tanpa akhir. Seolah dunia ini sudah kejam terhadapnya. Tentunya ini hanya cerita kecil yang sering kita jumpai di masyarakat pada umumnya. Teriakan-teriakan tak terdengar seperti ini pasti banyak dijumpai pada mereka yang memiliki ekonomi sempit. Pertanyaanya, apakah mereka tidak mengamuk? Jelas mengamuk bung! Tetapi ekspresi amukannya tidak seperti pertarungan di sidang DPR yang hampir terjadi adu jotos. Tidak pula sekejam pembantaian Amerika terhadap Irak. Bentuk amukannya dipendam di dalam dada, seolah bersikap dewasa terhadap kebijakan pemerintah. Ada keinginan untuk memberontak, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan seperti layaknya partai politik. Padahal jika mereka menyadari betul, kekuatan tertinggi adalah rakyat. Tinggal bagaimana rakyat menyatukan kekuatan itu, lalu menghantam para elit penguasa yang tuli dan buta. Bisakah kita kita gelisah seperti kegeliasahan yang dirasakan oleh Ibu Sunarsih?
Para mahasiswa dan ilmuwan kampus yang selama ini dianggap sebagai orang yang memiliki kesadaran tinggi telah berkoar-koar di sepanjang jalan. Mereka memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini telah terenggut oleh sebagian kepentingan oknum. Tetapi toh usaha mereka sia-sia belaka. Tak ada respon positif dari pemerintah, bahkan dengan demo-demo seperti itu pemerintah semakin kebal dan tahan banting. Ha, ha, ha, kayak barang dagangan saja.
Tak tertinggal masyakarat desa yang tidak mengerti apa-apa tiba-tiba terkena imbas dari musibah yang melanda bangsa ini. Bangsa yang telah mereka anggap sebagai nenek moyang dan leluhur agung. Bangsa yang telah merdeka selama 66 tahun tetapi rakyatnya masih saja dalam “belenggu hitam” oleh penguasa bejat. Lalu apa arti merdeka, kalau rakyatnya masih terjerat di dalam semak-semak rumput. Rezim Orde Baru telah mengekang akal pikiran manusia, asas tunggal yang harus dipakai di dalam hidup keseharian rakyat Indonesia hanyalah pancasila. Bagi mereka yang melawan akan dibunuh. Inikah bentuk kemerdekaan? Kemerdekaan yang telah melahirkan kekejaman terhadap rakyatnya. Ampuni kami, Tuhan.
Tak heran, jika kenaikan BBM dikaitkan dengan meledaknya bom Bali kedua. Kalau boleh diplesetkan, BBM adalah “Bom Bali Meledak”. Jika BBM naik maka bom bali akan naik (baca: meledak) pula. Ada juga yang mengatakan BBM adalah “Bola-Bali Mundak”. Sehingga sebagian orang mengatakan SBY-JK adalah singkatan dari ”Susah Bensin Ya-Jalan Kaki”. Ha, ha, ha...
Di tengah banyaknya musibah yang menimpa bangsa
Sedikit lelucon. Di sebuah toko ada sederetan jam yang dijual. Semua jam menunjukkan karakter negaranya masing-masing. Jenis jamnya ada yang lambat, tapi ada pula yang kencang. Ketika seorang pembeli menanyakan mana jam milik orang Indonesia. Si penjual mengatakan, tidak ada. Lalu ke mana? Dipakai untuk baling-baling helikopter. Sebuah ledekan yang menunjukkan tingkat korupsi Indonesia begitu cepat dan tinggi. Ada-ada saja, Mas.
Ini pertanda apa wahai bangsaku, bangsa yang hingga kini masih saja mengagung-agungkan demokarsi. Seolah demokrasi di atas segala-galanya. Tapi sudahkah paham apa itu demokrasi? Jangan-jangan selama ini kita telah salah memahami apa itu demokrasi. Pernah ada seorang mahasiswa yang berdemo dan berkoar-koar tentang demokrasi. Kemudian menggedor pintu salah satu ruangan kelas kampus dan memaksa orang yang sedang hikmat belajar untuk ikut berdemokrasi. Inikah tindakan demokrasi? Secara tidak langsung dia tidak konsisten dengan pendiriannya. Berfikir demokrasi tapi tidak bertindak demokrasi.
Kegelisahan yang dialami Ibu Sunarsih di atas mungkin tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lebih besar seperti gempa dan tindakan kriminalitas. Tapi jika teriakan-teriakan kecil itu sudah di ambang batas dan tidak memiliki kesabaran lagi, maka mereka bisa menjadi orang yang lebih brutal dari permainan musik underground. Puncak kesabaran ada batasnya, Bung. Jika batas itu sudah lewat maka singa hutan bisa dihantam.
Wahai bangsaku, lihatlah kami yang berada di pinggiran desa ini. Jangan membuat kami yang sudah sengsara menjadi lebih sengsara. Habis sudah kesabaran di dalam dada ini. Dada yang setiap hari ditusuk oleh duri-duri kecil. Saatnya bagi kami untuk menuntut kepada anda wahai pemerintah. Kami berhak atas diri anda, karena anda adalah perwakilan rakyat yang memperjuangkan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atas nama kepentingan rakyat. Inilah kejahatan yang harus segera dibunuh.
Dunia sudah kejam. Dengan kekejaman itu wajar jika ada seseorang yang akhirnya memilih jalan bunuh diri. Mungkin inilah pilihan terbaik baginya dari pada dia tersiksa di dunia. Bagi mereka yang bunuh diri mungkin mengatakan, “Tuhan Maha Bijaksana terhadap keputusan yang aku pilih. Biarlah orang menilai semaunya sendiri. Inilah jalan yang terbaik bagiku. Jalan yang telah Engkau berikan padaku, karena Engkaulah pembuat takdir itu.”
Janganlah bersedih, karena kesediahan itu akan datang setiap hari. Buatlah hari-harimu dengan plesetan-plesetan ceria. Niscaya kau akan tetap bahagia. Tugas kita sekarang adalah bangkit. Hai, Pemerintah! Orang yang kerjaannya suka merintah. Merintah rakyat yang tertindas. Janganlah engkau yang berada di istana membuat kebijakan seenaknya sendiri. Pikirkan kami yang berada di sudut desa terpencil. Kami punya anak dan istri yang setiap hari selalu meminta keinginannya masing-masing. Ya, Allah berilah keadilan kepada kami, kepada bangsa Indonesia, bangsa yang sedih bin pesetan.
(Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Idul Adha Gunung Kidul)
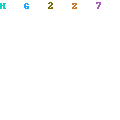

0 komentar:
Posting Komentar